Penyebab Terjadinya Konflik Politik yang Perlu Anda Tahu
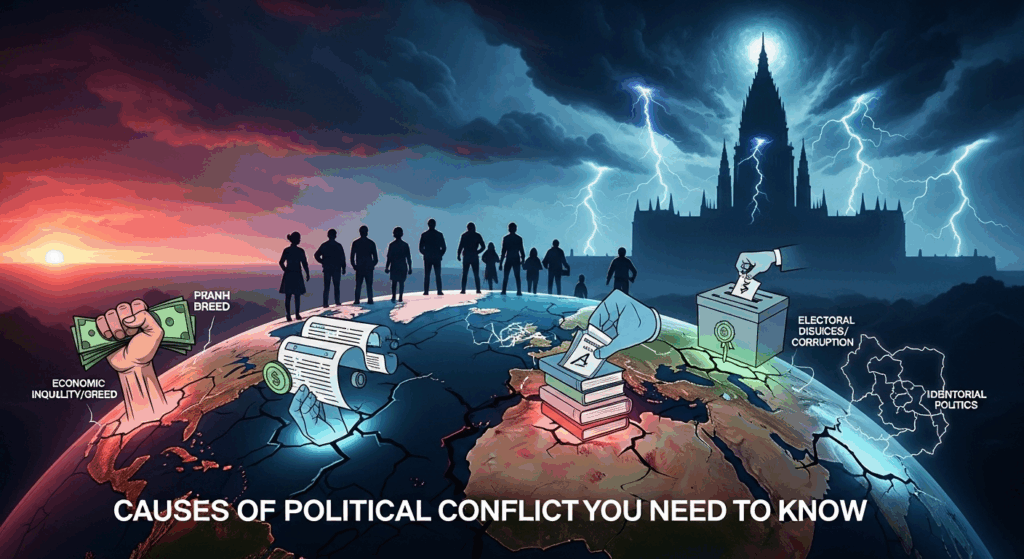
Konflik politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan bernegara. Dari debat sengit di parlemen hingga demonstrasi massa di jalanan, perbedaan pandangan politik seringkali memicu ketegangan. Namun, ketika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, ia dapat bereskalasi menjadi konflik terbuka yang merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan bangsa. Memahami secara mendalam berbagai penyebab terjadinya konflik politik adalah langkah awal yang krusial untuk membangun masyarakat yang lebih stabil, adil, dan demokratis. Artikel ini akan mengupas tuntas faktor-faktor fundamental yang seringkali berada di balik layar pertarungan politik, mulai dari persoalan ekonomi hingga perebutan kekuasaan yang tak kunjung usai.
Faktor Ekonomi sebagai Akar Permasalahan Utama
Ekonomi seringkali menjadi panggung utama di mana benih-benih konflik politik ditanam. Isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya bukanlah sekadar angka statistik, melainkan realitas pahit yang dialami oleh sebagian besar masyarakat. Ketika kondisi ekonomi memburuk atau ketika kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir elite, rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan akan menyebar luas. Sentimen ini menjadi bahan bakar yang sangat mudah disulut oleh para aktor politik untuk memobilisasi massa dan menantang pemegang kekuasaan.
Pada akhirnya, kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara ekonomi akan mencari saluran politik untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mereka mungkin membentuk gerakan sosial, mendukung partai oposisi, atau bahkan melakukan aksi protes. Jika institusi politik yang ada gagal merespons tuntutan ini secara efektif dan adil, potensi eskalasi menuju konflik terbuka menjadi sangat besar. Oleh karena itu, ketimpangan ekonomi yang tidak teratasi adalah salah satu bom waktu paling berbahaya dalam politik suatu negara.
Ketimpangan Distribusi Sumber Daya
Ketimpangan distribusi sumber daya merujuk pada kondisi di mana kekayaan, peluang, dan aset produktif (seperti tanah, modal, dan akses pendidikan berkualitas) terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok. Sementara itu, mayoritas penduduk kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Situasi ini menciptakan jurang sosial yang dalam antara "si kaya" dan "si miskin", yang seringkali berhimpitan dengan pembagian geografis (kota vs desa) atau etnis. Perasaan diperlakukan tidak adil dan ditinggalkan oleh negara menjadi sangat kuat di kalangan kelompok yang terpinggirkan.
Rasa ketidakadilan ini menjadi fondasi bagi munculnya konflik politik. Kelompok yang merasa hak-hak ekonominya terabaikan akan cenderung melihat sistem politik yang ada sebagai penyebab penderitaan mereka. Mereka akan menuntut perubahan struktural, redistribusi kekayaan, dan kebijakan yang lebih pro-rakyat. Tuntutan ini, jika diabaikan oleh elite yang berkuasa yang menikmati status quo, akan memicu polarisasi masyarakat. Pertarungan politik tidak lagi sekadar tentang program, tetapi menjadi perjuangan antara kelas-kelas sosial yang berbeda kepentingan.
Kebijakan Ekonomi yang Tidak Pro-Rakyat
Kebijakan ekonomi yang dirancang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh lapisan masyarakat adalah sumber konflik yang signifikan. Contohnya, kebijakan liberalisasi perdagangan yang mungkin menguntungkan industri besar di perkotaan, namun di saat yang sama mematikan usaha kecil dan petani di pedesaan. Contoh lain adalah pencabutan subsidi energi yang memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah tanpa adanya jaring pengaman sosial yang memadai. Kebijakan semacam ini menciptakan "pemenang" dan "pecundang" secara sistematis.
Kelompok "pecundang" yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut secara alami akan melawan. Perlawanan ini bisa dimulai dari kritik di media sosial, unjuk rasa damai, hingga pembangkangan sipil. Aktor-aktor politik oposisi seringkali memanfaatkan momentum ini untuk menggalang dukungan dan menyerang pemerintah. Isu ekonomi yang teknis dengan cepat berubah menjadi narasi politik yang emosional: "pemerintah tidak peduli rakyat kecil" atau "kebijakan ini pesanan asing". Narasi inilah yang memobilisasi massa dan mempertajam konflik antara pendukung dan penentang pemerintah.
Perbedaan Ideologi dan Politik Identitas
Di luar faktor ekonomi, arena pertarungan gagasan dan identitas merupakan penyebab konflik politik yang sama kuatnya. Ideologi adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan gagasan tentang bagaimana masyarakat dan negara seharusnya diatur. Perbedaan fundamental antara ideologi, misalnya antara sosialisme yang menekankan kesetaraan kolektif dan liberalisme yang menomorsatukan kebebasan individu, secara inheren menciptakan potensi konflik. Masing-masing ideologi menawarkan visi yang berbeda tentang keadilan, peran pemerintah, dan hak-hak warga negara.
Konflik menjadi semakin rumit dan berbahaya ketika ideologi berkelindan dengan politik identitas. Politik identitas adalah praktik di mana individu atau kelompok mendefinisikan kepentingan politik mereka berdasarkan identitas kolektif seperti agama, suku, ras, atau etnis. Ketika identitas ini dipolitisasi, batas antara "kita" dan "mereka" menjadi sangat tegas dan emosional. Isu-isu kebijakan yang seharusnya bisa diperdebatkan secara rasional berubah menjadi pertarungan simbolik yang menyangkut harga diri dan eksistensi kelompok.
Bahaya terbesar dari politisasi identitas adalah kecenderungannya untuk mengubah lawan politik menjadi musuh. Kompromi menjadi sulit dicapai karena setiap konsesi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap identitas kelompok. Narasi yang dibangun seringkali bersifat absolut dan menstigmatisasi kelompok lain sebagai ancaman. Akibatnya, dialog yang konstruktif mati dan digantikan oleh saling curiga dan kebencian, sebuah kondisi yang sangat subur bagi meletusnya konflik horizontal di tengah masyarakat.
Benturan Antara Ideologi Fundamentalisme dan Sekularisme
Salah satu contoh paling jelas dari benturan ideologi adalah pertarungan antara fundamentalisme dan sekularisme. Fundamentalisme, terutama dalam konteks keagamaan, meyakini bahwa nilai-nilai dan hukum agama harus menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara. Mereka memperjuangkan agar negara secara formal mengadopsi syariat atau aturan suci tertentu. Sebaliknya, sekularisme berpandangan bahwa urusan negara dan agama harus dipisahkan untuk menjamin netralitas negara terhadap semua warga negara yang berbeda keyakinan.
Konflik antara dua kutub ideologi ini menyentuh aspek paling dasar dalam sebuah negara: identitas dan hukum. Pertanyaannya menjadi: "Apakah kita negara agama atau negara kebangsaan?". Pertarungan ini sering terjadi dalam perumusan konstitusi, undang-undang (seperti hukum keluarga atau pidana), dan kebijakan publik (misalnya terkait pendidikan dan moralitas). Karena menyangkut keyakinan yang mendalam, kompromi sangat sulit ditemukan dan potensinya untuk menciptakan perpecahan sosial yang dalam sangatlah besar.
Politisasi Identitas untuk Mobilisasi Massa
Politisasi identitas adalah strategi yang digunakan oleh elite politik untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara mengeksploitasi sentimen identitas kelompok. Caranya adalah dengan membangun narasi bahwa kelompok identitas mereka sedang terancam, didiskriminasi, atau hak-haknya dirampas oleh kelompok lain. Dengan narasi ini, mereka membangun solidaritas internal yang kuat dan mengarahkan kemarahan kolektif kepada "musuh" yang telah diciptakan.
Praktik ini sangat berbahaya karena mengalihkan perhatian publik dari isu-isu substansial seperti kinerja pemerintah, korupsi, atau kebijakan ekonomi. Masyarakat menjadi lebih fokus pada siapa lawan dan siapa kawan berdasarkan suku atau agamanya, bukan berdasarkan gagasan atau rekam jejaknya. Dalam pemilu, misalnya, pemilih mungkin memilih kandidat bukan karena programnya yang bagus, melainkan karena "ia berasal dari kelompok kita". Hal ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menanam benih-benih kebencian antar-kelompok yang bisa meledak menjadi konflik kekerasan kapan saja.
Perebutan Kekuasaan dan Lemahnya Institusi Politik
Pada intinya, politik adalah tentang kekuasaan (power): siapa yang mendapatkannya, bagaimana cara menggunakannya, dan untuk tujuan apa. Perebutan kekuasaan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia menjadi penyebab konflik yang destruktif ketika proses perebutan tersebut tidak diatur oleh aturan main yang jelas, adil, dan ditaati oleh semua pihak. Di sinilah peran institusi politik menjadi sangat sentral. Institusi politik seperti komisi pemilihan umum, lembaga peradilan, parlemen, dan aparat penegak hukum berfungsi sebagai wasit dalam permainan politik.
Ketika institusi-institusi ini lemah, tidak independen, atau korup, mereka gagal menjalankan fungsi wasitnya. Pemilu yang curang, putusan pengadilan yang bisa dibeli, atau aparat keamanan yang berpihak pada penguasa akan menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem. Kelompok yang merasa dicurangi tidak akan lagi melihat jalur institusional sebagai cara yang efektif untuk memperjuangkan kepentingannya. Mereka akan kehilangan kepercayaan pada demokrasi itu sendiri dan mulai mencari alternatif di luar sistem.
Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai pertarungan politik zero-sum game, di mana kemenangan satu pihak berarti kekalahan total bagi pihak lain. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau berbagi kekuasaan. Kelompok yang kalah akan merasa eksistensinya terancam, sementara kelompok yang menang akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Inilah lingkungan yang ideal bagi terjadinya instabilitas politik kronis, kudeta, atau bahkan perang saudara, karena tidak ada lagi mekanisme damai yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa.
| Karakteristik | Institusi Politik Kuat & Demokratis | Institusi Politik Lemah & Rapuh |
|---|---|---|
| Pemilu | Bebas, adil, transparan, dan hasilnya dihormati semua pihak. | Sarat dengan kecurangan, intimidasi, dan hasilnya sering digugat. |
| Supremasi Hukum | Hukum berlaku sama untuk semua, tanpa pandang bulu. Peradilan independen. | Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Peradilan mudah diintervensi. |
| Birokrasi | Profesional, netral, dan berbasis meritokrasi. | Penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan dipolitisasi. |
| Partisipasi Publik | Ruang kebebasan berpendapat dan berserikat dijamin. Kritik dianggap masukan. | Kritik dibungkam, aktivis diintimidasi, dan ruang sipil menyempit. |
| Penyelesaian Sengketa | Ada mekanisme yang jelas dan terpercaya (misalnya Mahkamah Konstitusi). | Sengketa diselesaikan melalui pengerahan massa atau kekerasan. |
Buruknya Tata Kelola Pemerintahan (Governance)
Tata kelola pemerintahan yang buruk merupakan biang keladi dari berbagai masalah yang memicu konflik politik. Ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari korupsi yang merajalela, birokrasi yang tidak efisien, hingga pelayanan publik yang tidak memadai. Ketika warga negara harus membayar suap untuk mendapatkan layanan dasar seperti KTP, izin usaha, atau bahkan perawatan kesehatan, kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan terkikis habis. Mereka melihat negara bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai predator.
Korupsi secara khusus memiliki daya rusak yang luar biasa. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan raya justru masuk ke kantong pribadi pejabat dan kroni-kroninya. Hal ini tidak hanya menciptakan kerugian finansial, tetapi juga melanggengkan ketimpangan ekonomi dan merusak rasa keadilan. Korupsi menjadi simbol nyata dari kegagalan sistem dan pengkhianatan para pemimpin terhadap amanat rakyat, memicu kemarahan publik yang dapat dengan mudah dieksploitasi untuk tujuan politik.

Selain korupsi, kegagalan pemerintah dalam menegakkan hukum (law enforcement) juga menjadi sumber konflik. Ketika pelaku kejahatan, terutama yang memiliki beking politik, tidak tersentuh hukum, masyarakat akan merasa tidak aman dan tidak dilindungi. Main hakim sendiri atau pembentukan milisi swadaya bisa menjadi respons atas kekosongan peran negara. Ketidaktegasan dalam menindak kelompok-kelompok intoleran yang melakukan kekerasan juga dapat memicu konflik horizontal, karena kelompok korban merasa negara telah membiarkan mereka diserang.
Korupsi Sistemik dan Ketidakpercayaan Publik
Korupsi sistemik berarti praktik korupsi tidak lagi dilakukan oleh oknum-oknum secara sembunyi-sembunyi, melainkan telah menjadi bagian dari cara kerja sistem itu sendiri. Ia terjadi secara terstruktur, masif, dan melibatkan banyak pihak di berbagai level, dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Dalam kondisi seperti ini, upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit karena para pelakunya saling melindungi satu sama lain.
Dampak langsung dari korupsi sistemik adalah hancurnya kepercayaan publik (public trust) kepada seluruh institusi negara. Rakyat menjadi apatis dan sinis terhadap politik, merasa bahwa siapa pun yang berkuasa akan sama saja perilakunya. Apatisme ini berbahaya bagi kesehatan demokrasi. Namun, di sisi lain, sinisme ini juga bisa bermutasi menjadi kemarahan massal yang eksplosif. Sebuah skandal korupsi besar yang terungkap ke publik bisa menjadi percikan api yang memicu gelombang protes besar-besaran yang menuntut reformasi total.
Kegagalan Negara dalam Menyediakan Pelayanan Dasar
Negara modern pada dasarnya mengikat kontrak sosial dengan warganya: warga membayar pajak, dan sebagai imbalannya, negara menyediakan keamanan dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketika negara gagal memenuhi bagiannya dari kontrak ini, legitimasinya di mata warga akan merosot tajam. Kegagalan ini bisa terasa sangat konkret: jalanan yang rusak parah, sekolah yang hampir rubuh, rumah sakit tanpa obat-obatan, atau air bersih yang sulit diakses.
Ketidakmampuan memberikan pelayanan dasar seringkali terkait erat dengan masalah korupsi dan alokasi anggaran yang tidak tepat. Daerah-daerah yang terpencil atau dihuni oleh kelompok minoritas seringkali menjadi korban utama dari kegagalan ini. Perasaan dianaktirikan oleh pemerintah pusat dapat mendorong munculnya gerakan separatisme atau tuntutan otonomi yang lebih luas. Konflik ini pada dasarnya adalah protes terhadap negara yang dianggap telah lalai dalam menjalankan kewajiban fundamentalnya.
Peran Faktor Eksternal dan Dinamika Global
Konflik politik dalam suatu negara jarang sekali terjadi di dalam ruang hampa. Ia seringkali dipengaruhi, diperburuk, atau bahkan dipicu oleh faktor-faktor yang berasal dari luar batas negara. Dalam dunia yang semakin terhubung, intervensi asing, persaingan geopolitik antar negara besar, dan arus informasi global memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik domestik. Negara-negara besar mungkin memiliki kepentingan strategis atau ekonomi di negara lain, dan tidak segan-ragu untuk ikut campur demi mengamankan kepentingannya.
Bentuk intervensi asing ini bisa sangat beragam. Mulai dari yang paling keras seperti intervensi militer, hingga yang lebih lunak seperti pemberian bantuan ekonomi bersyarat, pendanaan untuk kelompok oposisi, atau pelaksanaan operasi intelijen. Tujuannya bisa untuk menggulingkan rezim yang tidak disukai, mendukung rezim yang pro terhadap kepentingan mereka, atau sekadar menciptakan instabilitas untuk melemahkan negara saingan. Kehadiran aktor eksternal ini seringkali memperumit dan memperpanjang durasi konflik politik internal.
Di era digital, medan pertempuran baru telah muncul: ruang informasi. Penyebaran hoax, disinformasi, dan propaganda melalui media sosial telah menjadi senjata yang ampuh untuk memecah belah masyarakat dan mendelegitimasi pemerintah. Operasi pengaruh ini bisa dilancarkan oleh aktor domestik maupun asing. Mereka mengeksploitasi polarisasi yang sudah ada, memperkuat narasi kebencian, dan menciptakan realitas alternatif yang membuat warga tidak lagi bisa membedakan mana fakta dan mana fiksi. Perang informasi ini secara langsung meracuni diskursus publik dan menghancurkan kemungkinan dialog yang sehat.
Intervensi Asing dan Kepentingan Geopolitik
Sebuah negara yang memiliki posisi geografis strategis atau kaya akan sumber daya alam (seperti minyak, gas, atau mineral langka) sangat rentan terhadap intervensi asing. Negara-negara adidaya akan bersaing untuk menanamkan pengaruhnya di negara tersebut demi mengamankan pasokan sumber daya atau jalur perdagangan. Mereka bisa melakukannya dengan mendukung salah satu faksi politik yang bersaing di dalam negeri.
Dukungan asing ini bisa berupa bantuan finansial, persenjataan, atau legitimasi diplomatik. Faksi yang menerima bantuan akan memiliki kekuatan lebih besar untuk melawan rival domestiknya. Akibatnya, konflik yang mungkin tadinya bisa diselesaikan secara internal menjadi "perang proksi" (proxy war) antara kekuatan-kekuatan global. Konflik menjadi lebih sulit diakhiri karena para pihak yang bertikai tidak lagi sepenuhnya otonom; mereka juga dikendalikan oleh kepentingan patron mereka di luar negeri.
Dampak Disinformasi dan Fake News di Era Digital
Media sosial telah mengubah cara informasi menyebar. Kecepatannya yang luar biasa dan kemampuannya untuk menargetkan audiens spesifik menjadikannya alat yang sangat efektif untuk propaganda. Aktor-aktor jahat, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat dengan mudah membuat dan menyebarkan konten fake news yang dirancang untuk membangkitkan amarah, ketakutan, dan kebencian. Algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten yang paling memancing emosi turut mempercepat penyebaran disinformasi ini.
Dampaknya terhadap politik sangat merusak. Warga yang terus-menerus terpapar disinformasi akan hidup dalam "gelembung filter" (filter bubble), di mana mereka hanya mendengar pandangan yang mengkonfirmasi keyakinan mereka. Mereka menjadi semakin tidak percaya pada media arus utama, pemerintah, dan bahkan pakar. Polarisasi masyarakat semakin tajam, dan kepercayaan sosial hancur. Dalam atmosfer beracun seperti ini, setiap isu kecil dapat dengan mudah dipelintir menjadi pemicu konflik besar.
FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan
Q: Apa perbedaan antara konflik politik dengan konflik sosial?
A: Konflik politik secara spesifik berpusat pada perebutan kekuasaan negara, pengaruh terhadap kebijakan publik, dan sumber daya yang dikontrol oleh negara. Para aktornya adalah partai politik, pemerintah, kelompok kepentingan, dan gerakan politik. Sementara itu, konflik sosial memiliki cakupan yang lebih luas, bisa terjadi antar kelompok masyarakat karena perbedaan status sosial, ekonomi, budaya, atau agama, tanpa harus secara langsung bertujuan merebut kekuasaan negara. Namun, kedua jenis konflik ini seringkali tumpang tindih; konflik sosial yang tidak tertangani dapat dengan mudah menjadi konflik politik, dan sebaliknya.
Q: Apakah konflik politik selalu bersifat negatif dan merusak?
A: Tidak selalu. Dalam kadar yang sehat dan terkelola dalam institusi demokrasi, konflik politik adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Perbedaan pendapat, debat kebijakan, dan kompetisi dalam pemilu adalah bentuk konflik yang konstruktif. Ia memungkinkan adanya kontrol terhadap kekuasaan (check and balance), menyalurkan aspirasi yang beragam, dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik. Konflik menjadi negatif dan destruktif ketika ia keluar dari koridor aturan hukum, menggunakan cara-cara kekerasan, dan bertujuan untuk meniadakan eksistensi lawan politik, bukan lagi untuk berkompetisi gagasan.
Q: Bagaimana cara terbaik untuk mencegah eskalasi konflik politik?
A: Mencegah eskalasi memerlukan pendekatan multi-lapis. Kuncinya adalah dengan memperkuat institusi demokrasi dan supremasi hukum. Ini termasuk memastikan pemilu yang adil, peradilan yang independen, dan aparat yang netral. Selain itu, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan untuk memberantas korupsi, serta aktif mempromosikan dialog antar-kelompok dan literasi digital untuk melawan disinformasi.
Q: Mengapa perebutan kekuasaan sering dianggap sebagai penyebab utama konflik politik?
A: Karena kekuasaan negara memberikan otoritas untuk membuat keputusan yang mengikat seluruh masyarakat dan mengontrol sumber daya yang sangat besar. Pihak yang memegang kekuasaan dapat menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan melalui kebijakan, alokasi anggaran, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, taruhannya sangat tinggi. Ketika mekanisme untuk memperoleh dan mentransfer kekuasaan secara damai (seperti pemilu) tidak lagi dipercaya, maka kelompok-kelompok politik akan cenderung menggunakan cara-cara non-demokratis, termasuk kekerasan, untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan tersebut.
Kesimpulan
Penyebab terjadinya konflik politik adalah sebuah fenomena yang kompleks dan multifaset, jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ia merupakan hasil dari interaksi rumit antara ketimpangan ekonomi yang dalam, benturan ideologi dan politisasi identitas, perebutan kekuasaan di tengah institusi yang rapuh, tata kelola pemerintahan yang buruk, serta pengaruh dari dinamika eksternal. Faktor-faktor ini saling terkait dan seringkali saling memperkuat, menciptakan lingkaran setan instabilitas yang sulit diputus.
Memahami akar-akar permasalahan ini bukan berarti menjustifikasi kekerasan atau perpecahan, melainkan untuk mencari solusi yang lebih fundamental. Jalan menuju stabilitas politik jangka panjang terletak pada komitmen bersama untuk membangun negara yang berlandaskan supremasi hukum, institusi demokrasi yang kuat dan dipercaya, kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial, serta masyarakat yang kritis dan mampu berdialog secara dewasa. Tanpa upaya serius untuk mengatasi akar-akar masalah ini, konflik politik akan terus menjadi hantu yang mengancam keutuhan bangsa.
***
Ringkasan Artikel
Artikel ini mengupas secara mendalam berbagai penyebab terjadinya konflik politik yang seringkali kompleks dan saling berkaitan. Faktor utama yang dibahas adalah ketimpangan ekonomi dan distribusi sumber daya yang tidak merata, yang menciptakan ketidakpuasan luas di tengah masyarakat. Selain itu, perbedaan ideologi (seperti fundamentalisme vs sekularisme) dan politisasi identitas (agama, suku, ras) menjadi pemicu kuat yang mempertajam perpecahan sosial. Artikel ini juga menyoroti bagaimana perebutan kekuasaan yang tidak diatur oleh institusi politik yang lemah dapat mengubah kompetisi sehat menjadi pertarungan destruktif. Tata kelola pemerintahan yang buruk, terutama korupsi sistemik dan kegagalan menyediakan layanan publik, semakin mengikis kepercayaan rakyat. Terakhir, dibahas pula peran faktor eksternal seperti intervensi asing serta dampak disinformasi dan hoax di era digital yang memperburuk konflik domestik. Kesimpulannya, solusi untuk meredam potensi konflik terletak pada penguatan institusi demokrasi, penegakan supremasi hukum, dan penerapan kebijakan yang adil dan inklusif.

